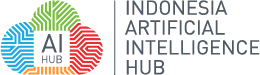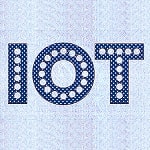CTO Deloitte: 93% Anggaran AI untuk Teknologi, SDM Tertinggal
- Rita Puspita Sari
- •
- 20 Des 2025 18.56 WIB

Gedung Deloitte
Transformasi artificial intelligence (AI) kini memasuki fase baru. Jika sebelumnya perusahaan masih berada pada tahap uji coba dan eksperimen, saat ini banyak organisasi mulai mendorong penerapan AI dalam skala besar yang diharapkan berdampak langsung pada bisnis. Namun di balik percepatan tersebut, muncul persoalan mendasar yang justru berpotensi menghambat keberhasilan transformasi AI itu sendiri.
Berdasarkan Laporan Tahunan Tech Trends Report Deloitte edisi ke-17, Chief Technology Officer (CTO) Deloitte, Bill Briggs, mengungkap fakta yang mengejutkan: rata-rata perusahaan menghabiskan sekitar 93% anggaran AI untuk teknologi, sementara hanya 7% dialokasikan untuk pengembangan SDM. Ketimpangan ini, menurut Briggs, menjadi kesalahan besar yang berulang dalam setiap gelombang adopsi teknologi baru.
Terlalu Fokus pada Teknologi, Lupa Cara Menggunakannya
Briggs menilai, mayoritas perusahaan terlalu terobsesi pada aspek teknis AI, seperti model AI, chip, hingga software pendukung. Semua itu dianggap sebagai “bahan utama” transformasi AI. Sayangnya, banyak organisasi melupakan “resep” agar bahan tersebut bisa menghasilkan nilai nyata.
“Budaya kerja, alur proses, pelatihan karyawan, dan perubahan cara berpikir justru sering diabaikan,” ujarnya.
Briggs mengibaratkan kondisi ini seperti ingin memasak hidangan kompleks tanpa memahami resepnya. Bahan-bahan tersedia lengkap, tetapi hasil akhirnya jauh dari yang diharapkan.
Pernyataan Briggs ini disampaikan dalam wawancara dengan majalah Fortune di kantor Deloitte, New York City, bertepatan dengan peluncuran Tech Trends Report Deloitte edisi ke-17. Laporan tahunan ini menjadi salah satu rujukan global dalam membaca arah perkembangan teknologi dan dampaknya bagi bisnis.
Briggs sendiri telah terlibat dalam laporan tersebut sejak awal kariernya di Deloitte, jauh sebelum perusahaan itu memiliki organisasi CTO. Saat itu, teknologi masih dianggap sebagai fungsi pendukung, bukan penggerak utama strategi bisnis.
“Dulu, teknologi hanyalah sekilas ide tentang apa yang mungkin akan kami lakukan lebih banyak di masa depan,” ujarnya.
Seiring waktu, peran teknologi berubah drastis. Namun menurut Briggs, cara berpikir banyak organisasi justru tertinggal, terutama dalam menyiapkan manusia untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Inersia Organisasi dan Pola Pikir Lama
Briggs menekankan bahwa masalah utama bukan terletak pada besar atau kecilnya investasi AI, melainkan pada inersia organisasi yang terlalu kuat. Banyak perusahaan enggan mengubah alur kerja yang sudah lama berjalan, meski teknologi yang digunakan telah berubah secara radikal.
Ia mengutip pernyataan tokoh ilmu komputer, Grace Hopper, yang menyebut bahwa kalimat paling berbahaya dalam bisnis adalah, “We’ve always done it this way.”
Menurut Briggs, rasio anggaran 93:7 mencerminkan ketergantungan perusahaan pada pola lama. Padahal, AI menuntut pendekatan baru yang menyentuh struktur kerja, peran karyawan, hingga cara pengambilan keputusan.
HR Dituntut Mendesain Ulang Pekerjaan
Pandangan Briggs sejalan dengan survei global dari firma konsultan Protiviti yang dirilis bersamaan dengan laporan Tech Trends. Fran Maxwell, pemimpin praktik konsultasi SDM global Protiviti, menegaskan bahwa fungsi HR memiliki peran krusial dalam transformasi AI.
“Organisasi harus mendesain ulang pekerjaan. Dan itu bukan kemampuan yang dimiliki sebagian besar fungsi HR saat ini,” kata Maxwell.
Ia menambahkan, tantangan talenta saat ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan lama. Keterampilan, struktur kerja, hingga definisi peran harus disesuaikan dengan era AI.
“Masalah talenta hari ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan talenta kemarin.” ujarnya.
Munculnya Shadow AI dan Krisis Kepercayaan
Ketimpangan antara investasi teknologi dan manusia mulai menimbulkan dampak nyata. Salah satunya adalah fenomena shadow AI, yakni penggunaan alat AI secara diam-diam oleh karyawan tanpa persetujuan perusahaan.
Berdasarkan laporan TrustID Deloitte, meskipun akses ke AI generatif di tempat kerja meningkat, tingkat penggunaan justru turun 15%. Sebanyak 43% karyawan mengaku melanggar kebijakan perusahaan dengan menggunakan alat AI tidak resmi.
Bahkan, survei lain menunjukkan bahwa di hingga 90% perusahaan, karyawan menggunakan AI tanpa sepengetahuan tim teknologi informasi (TI). Alasan utamanya sederhana: alat tidak resmi dianggap lebih mudah diakses dan lebih akurat dibanding solusi resmi perusahaan.
Kondisi ini memicu krisis kepercayaan. Tingkat kepercayaan karyawan terhadap AI perusahaan tercatat turun 38% hanya dalam rentang Mei hingga Juli 2025.
Sebaliknya, data menunjukkan bahwa pendekatan berpusat pada manusia membawa dampak signifikan. Karyawan yang mengikuti pelatihan AI langsung dan workshop melaporkan tingkat kepercayaan 144% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak mendapat pelatihan.
Menuju “HR untuk Agen AI”
Untuk mengatasi ketimpangan rasio 93:7 ini, Briggs menyarankan perubahan cara pandang yang lebih radikal. Ia menilai perusahaan perlu mulai memperlakukan agen AI dan robot layaknya “karyawan digital” yang memiliki sistem pengelolaan tersendiri.
Ketika organisasi mulai beralih dari “karyawan berbasis karbon” (manusia) ke “karyawan berbasis silikon” (AI, robot, dan sistem otonom), perusahaan perlu membangun proses seperti HR untuk AI. Ini mencakup pengelolaan kinerja, kepatuhan, hingga tanggung jawab hukum.
Briggs mengajukan skenario hipotetis: seorang manusia menciptakan satu agen AI, lalu agen tersebut menciptakan lima generasi agen berikutnya. Jika kesalahan terjadi di generasi kelima, siapa yang bertanggung jawab?
“Apa bentuk sanksinya? Apakah robotnya di-timeout dan diwajibkan mengikuti 10 jam pelatihan kepatuhan?” ujarnya setengah bercanda.
Ketakutan Akan Penyesalan Investasi
Di sisi lain, Briggs memahami ketakutan CEO dan dewan direksi akan buyer’s remorse—penyesalan setelah berinvestasi. Banyak pemimpin khawatir memilih teknologi atau vendor yang salah, lalu tertinggal ketika model AI baru muncul hanya dalam hitungan hari.
“Mereka takut berkomitmen di waktu yang salah,” kata Briggs.
Namun, menurutnya, sikap menunggu justru menjadi penghambat terbesar. Ia menggambarkan kondisi ini seperti mencoba menebak waktu terbaik di pasar saham—yang sering kali berujung pada kehilangan peluang.
Teknologi Siap, Manusia Harus Menyusul
Urgensi perubahan semakin terasa dengan hadirnya physical AI, yakni AI yang tidak hanya menghasilkan teks, tetapi juga mengendalikan robot, mesin, dan drone. Dampaknya jauh lebih nyata dan berisiko jika tidak dikelola dengan baik.
Contohnya, Hewlett Packard Enterprise (HPE) berhasil mempercepat proses pengambilan keputusan hingga 50 persen setelah menerapkan Zora AI, berkat integrasi teknologi dan kesiapan manusia yang seimbang.
Bagi Briggs, pesannya kepada para eksekutif sangat jelas. Teknologi AI sudah matang dan siap digunakan. Tantangannya kini bukan lagi soal kemampuan mesin, melainkan kesiapan manusia dan budaya organisasi.
Tanpa investasi serius pada pelatihan, perubahan proses, dan pembangunan kepercayaan, perusahaan berisiko memiliki teknologi mahal yang tidak digunakan secara optimal.
Seperti yang diingatkan Briggs, “Tidak peduli seberapa padat lalu lintasnya, semakin cepat Anda berangkat, semakin cepat Anda sampai.”