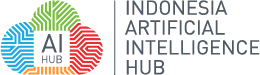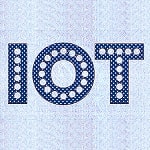Allister Frost: Mengatasi Kecemasan Tenaga Kerja di Era AI
- Rita Puspita Sari
- •
- 18 Jan 2026 12.01 WIB

Ilustrasi AI di Dunia Kerja
Integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini menjadi salah satu penentu utama keberhasilan perusahaan modern. Hampir semua sektor, mulai dari keuangan, manufaktur, logistik, hingga layanan publik, berlomba-lomba memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun di balik janji produktivitas dan inovasi tersebut, terdapat satu tantangan besar yang kerap dihadapi para pemimpin organisasi: kecemasan tenaga kerja.
Bagi banyak pemimpin perusahaan, penerapan AI sering kali dianggap sebagai proyek teknologi. Padahal, tantangan terbesar justru bukan terletak pada perangkat lunak, algoritma, atau infrastruktur digital, melainkan pada manusia yang menggunakannya. Sehebat apa pun teknologi yang diterapkan, tingkat adopsinya akan sangat ditentukan oleh penerimaan, pemahaman, dan kesiapan karyawan.
Fakta ini diperkuat oleh data dari TUC yang menunjukkan bahwa 51 persen orang dewasa di Inggris merasa khawatir terhadap dampak AI dan teknologi baru terhadap pekerjaan mereka. Kekhawatiran ini bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan berpotensi menjadi hambatan nyata bagi return on investment (ROI). Ketika karyawan menolak atau bersikap defensif terhadap AI, inovasi yang diharapkan justru bisa mandek.
Allister Frost, mantan pemimpin Microsoft dan pakar transformasi bisnis, menilai bahwa kecemasan ini sebagian besar berakar pada kesalahpahaman tentang apa itu AI dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teknologi tersebut.
Kesalahpahaman Besar tentang “Kecerdasan” AI
Salah satu kekeliruan paling umum dalam strategi perusahaan adalah menganggap AI generatif dan Large Language Models (LLM) sebagai entitas cerdas yang mampu berpikir dan bertindak layaknya manusia. Cara pandang ini memunculkan narasi bahwa mesin akan segera menggantikan peran manusia secara menyeluruh.
“Kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa AI sepintar namanya dan mampu melakukan tugas seperti manusia,” ungkap Frost. Menurutnya, AI pada dasarnya hanyalah sistem yang bekerja dengan mencocokkan pola dalam jumlah data yang sangat besar. Teknologi ini tidak memiliki kesadaran, intuisi, empati, maupun penilaian moral seperti manusia.
Frost menegaskan bahwa AI justru membuka peluang besar bagi manusia untuk bekerja lebih cerdas, berinovasi lebih cepat, dan mengeksplorasi cara-cara baru dalam menciptakan nilai. Namun peluang ini hanya bisa diwujudkan jika perusahaan mampu mengomunikasikan peran AI secara tepat kepada karyawan.
Ketika AI dipahami sebagai alat bantu, bukan sebagai “makhluk cerdas” yang mengancam eksistensi manusia, maka sudut pandang karyawan pun berubah. Dari yang semula merasa bersaing dengan mesin, menjadi melihat AI sebagai teknologi pendukung pekerjaan. “AI tidak dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, melainkan untuk melengkapinya,” tegas Frost.
Bahaya Menganggap AI sebagai Alat Pemangkasan Karyawan
Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian pemimpin, terutama di bidang keuangan dan operasional, melihat AI sebagai peluang untuk menekan biaya, khususnya biaya gaji. Otomatisasi sering dipersepsikan sebagai jalan pintas untuk mengurangi jumlah karyawan dan meningkatkan margin keuntungan dalam jangka pendek.
Namun, pendekatan ini dinilai Frost sebagai strategi yang berisiko. Menghilangkan tenaga kerja berpengalaman demi otomatisasi dapat merusak pengetahuan institusional yang selama ini menjadi aset berharga perusahaan. Pengalaman, intuisi bisnis, serta pemahaman mendalam terhadap pelanggan dan proses internal tidak bisa digantikan begitu saja oleh mesin.
“Terlalu sering bisnis memandang AI sebagai jalan pintas untuk mengurangi jumlah karyawan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya,” ujar Frost. Menurutnya, kerugian ekonomi dan sosial akibat hilangnya tenaga kerja terampil jauh lebih besar dibanding penghematan biaya yang diperoleh.
Kekhawatiran karyawan terkait hal ini memang beralasan. Data dari Acas menunjukkan bahwa 26 persen pekerja di Inggris menyebut potensi kehilangan pekerjaan sebagai ketakutan terbesar mereka terhadap penggunaan AI di tempat kerja. Meski demikian, sejarah membuktikan bahwa kemajuan teknologi cenderung mengubah jenis pekerjaan, bukan menghilangkannya secara massal.
“AI tidak akan menghapus pekerjaan secara sembarangan, melainkan akan mengubah cara kita bekerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan,” kata Frost.
AI sebagai Alat Pendukung, Bukan Pengganti
Agar integrasi AI berjalan sukses, Frost menekankan pentingnya mengubah cara pandang perusahaan dalam mengidentifikasi penggunaan AI. Alih-alih mencari peran atau posisi yang bisa dihilangkan, pemimpin seharusnya fokus pada tugas-tugas rutin, berulang, dan bernilai rendah yang selama ini menghambat produktivitas.
“AI sangat efektif untuk mengotomatiskan pekerjaan yang membosankan dan memakan waktu,” jelas Frost. Dengan otomatisasi ini, tenaga manusia dapat dialihkan ke pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, analisis mendalam, dan interaksi manusiawi.
Ketika AI mengambil alih tugas-tugas repetitif, karyawan memiliki ruang untuk meningkatkan keterampilan dan beralih ke peran yang lebih kompleks. Kemampuan seperti berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, pengambilan keputusan etis, dan perencanaan strategis masih menjadi keunggulan manusia yang tidak bisa ditiru oleh mesin.
Inilah konsep augmentasi, di mana AI berfungsi sebagai alat pendukung yang memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga motivasi dan rasa aman karyawan.
Mengatasi Change Fatigue dan Membangun Kepercayaan
Penolakan terhadap AI sering kali bukan semata-mata karena teknologi itu sendiri, melainkan akibat kelelahan terhadap perubahan atau change fatigue. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi mengalami gelombang transformasi digital yang cepat dan beruntun, sehingga karyawan merasa lelah dan kewalahan.
Dengan 14 persen pekerja Inggris secara spesifik khawatir terhadap dampak AI pada pekerjaan mereka saat ini, transparansi dan tata kelola yang jelas menjadi kunci. Para pemimpin perlu menyadari bahwa menolak atau menunda integrasi AI justru dapat menghambat kemajuan dan mengurangi peluang inovasi.
Solusi yang ditawarkan Frost adalah keterlibatan aktif karyawan. Melibatkan mereka dalam diskusi tentang peran AI, tujuan implementasi, serta dampaknya terhadap pekerjaan sehari-hari dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan membangun kepercayaan.
Pendekatan ini menuntut lebih dari sekadar kebijakan satu arah dari manajemen. Perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang inklusif, di mana karyawan merasa aman untuk belajar, bereksperimen, dan beradaptasi dengan teknologi baru tanpa rasa takut akan kehilangan pekerjaan.
Ketika transparansi dan partisipasi terbangun, kecemasan pun dapat ditekan, dan seluruh tim menjadi lebih siap untuk memanfaatkan potensi AI secara optimal.
Menyiapkan Tenaga Kerja untuk Masa Depan Berbasis AI
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kemajuan teknologi selalu diiringi resistansi. Namun, manusia juga selalu berhasil beradaptasi. AI memang membawa perubahan yang signifikan, tetapi pada dasarnya merupakan bagian dari evolusi teknologi yang tak terhindarkan.
Bagi para pemimpin perusahaan, kunci keberhasilan terletak pada investasi terhadap ketahanan organisasi dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan membingkai AI sebagai alat transformasi yang memberdayakan manusia, bukan ancaman, perusahaan dapat melindungi talenta sekaligus memodernisasi operasional.
Sebagai penutup, Frost merangkum pendekatan strategis agar integrasi AI berjalan sukses: mengubah narasi tentang AI, mengidentifikasi peluang augmentasi, berinvestasi pada keterampilan manusia, serta membangun dialog yang terbuka dan transparan.
“Tujuan saya adalah menyelamatkan satu juta kehidupan kerja dengan menunjukkan bahwa AI bekerja paling baik ketika memberdayakan manusia, bukan menggantikannya,” pungkas Frost.